
Mendengar kata riset, sebagian orang bergidik. Seolah kata riset itu punya energi negatif level tinggi. Atau sesuatu yang di luar jangkauan. Di awang-awang seperti gelar profesor. Faktanya, nyaris setiap saat sesungguhnya kita melakukan kegiatan yang merupakan bagian dari riset. Panca indera kita adalah alat riset yang sudah menempel sejak lahir. Dulu, saya pun beranggapan riset sebagai suatu yang rumit dan canggih. Setelah tahu aslinya, senyum-senyum sendiri. Bahagia.
Tidak perlu saya sampaikan definisi riset. Silakan bergaul dengan mbah Google. Pada dasarnya, kegiatan riset tidak lebih tinggi daripada membaca, melihat, mengamati, bertanya, meng-gali, dan mendalami… Kepo deh. Membaca bukan pada level paling dasar, tapi tingkat lanjut. Bukan sekadar membaca yang tersurat. Tapi juga tersirat. Bahkan sebelum tersirat dan tersurat. Atau tidak tersirat dan tidak juga tersurat. Tidak perlu bingung. Silakan lebih banyak membaca, melihat, mengamati, bertanya, menggali, dan mendalami suatu hal, maka Anda akan cepat paham.
Proses kreatif saya menulis selalu diawali oleh riset. Riset pustaka; membaca berbagai literatur terkait topik apa yang akan kita tulis. Sebanyak-banyaknya. Atau secukupnya, sesuai kebutuhan. Tentang inti topik atau hal yang melingkupinya. Biar tulisan menjadi kaya.
Riset media massa; membaca berbagai informasi yang dimuat di media massa. Sekarang, media massa makin beragam jenisnya. Bukan hanya cetak dan elektronik, juga media internet dan media sosial.
Riset dokumen; membaca apa pun yang terekam terkait topik dalam bentuk dokumen baik tertulis, terrekam suaranya, atau tervideokan. Menjadikan tulisan semakin kuat. Observasi dengan cara melihat, mendengar, dan merasakan langsung dari tempat kejadian. Terakhir adalah wawancara, baik wawancara narasumber utama (primer), narasumber sekunder, maupun narasumber pendukung. Baik wawancara biasa maupun wawancara mendalam.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa melakukan itu semua bukan? Biasa membaca dan biasa berdiskusi dengan orang lain. Ngobrol ke sana ke mari dengan banyak orang. Bahkan Terry Pratchett salah satu novelis terkemuka Inggris berpendapat, riset terbaik adalah berbicara dengan orang lain (dialog dan diskusi). Jadi, jangan abaikan interaksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah bagian dari riset.
Kita juga biasa membaca buku, dokumen, dan sering juga mengalami dan merasakan sesuatu secara langsung. Jika semua dikumpulkan dan dipilah sesuai dengan topiknya, berapa banyak yang Anda dapatkan setiap hari? Setiap pekan? Setiap bulan? Begitu banyak topik yang bisa Anda tuliskan dari hasil riset sehari-hari itu. Belum lagi ditambah dengan pengalaman Anda sendiri.
Pengalaman sendiri merupakan hal bersifat empirik yang biasanya punya nilai lebih tinggi daripada hasil riset yang lain. Bisa juga menjadi pelengkap. Atau malah bumbu penyedap yang luar biasa. Tidak jarang menjadi inti. Riset yang lain sebagai pelengkap dan bumbu. Tidak salah jika beberapa penulis tersohor mengatakan, “Setiap orang punya satu topik menulis yang bisa dijadikan buku: Pengalaman hidupnya sendiri.”
Setiap kali menulis, saya pasti melakukan riset, mengumpulkan informasi selengkap mungkin, dan mensistemasikannya. Bukan sekadar membaca atau mengamati. Pengalaman lebih dari 10 tahun sebagai wartawan, mengajarkan saya betapa pentingnya riset. Wawancara mendalam sudah biasa saya lakukan dan begitu bertuah sebagai salah satu kemampuan dasar dalam menulis.
Jika Anda sudah bisa membaca, lalu ngobrol bergizi (sebutan saya untuk wawancara mendalam), maka Anda sudah bisa menulis. Bahan Anda sudah mencukupi. Membaca dan wawancara adalah bagian dari riset.
Seperti saya tuangkan pada bagian sebelumnya, riset melalui membaca pasti saya lakukan sebelum menulis buku. Sebanyak 20 – 40 bahan bacaan (termasuk buku) menjadi pengisi kepala sebelum menuangkannya dalam tulisan. Dalam tahapan menulis buku, mencari dan mengumpulkan bahan ini merupakan bagian penting dari pratulis, atau tahapan sebelum memulai proses menulis. Dalam beberapa kasus, proses mencari bahan jauh lebih lama dibanding proses penulisannya. Saya tidak akan mulai menulis sampai bahan-bahan itu terkumpul. Minimal 80%-nya.
Bahan-bahan itu berintegrasi dengan bahan hasil riset lainnya berupa wawancara, observasi, dan atau daya pikir pribadi. Kemampuan analisis menjadi salah satu yang harus dimiliki, selain interpretasi. Tentu, dalam hal ini ketika menulis naskah nonfiksi. Kalau menulis fiksi lain lagi ceritanya. Selain riset-riset tersebut, kemampuan imajinasi, menyusun alur, dan merangkai kata indah menjadi ukurannya.
Salah satu proses pengumpulan bahan paling panjang yang saya lakukan adalah ketika menyusun buku Belajar Uji Nyali dari Benny Moerdani. Saya mendapatkan tulisan lebih dari 100 kerabat, kawan, dan anak buah pak Benny. Diskusi dengan keluarga dan orang dekatnya, serta membaca semua buku yang berisi tentang perjalanan karier jenderal intelijen itu. Dan tentu saja, beragam bahan bacaan yang berserak di dunia maya. Butuh waktu lebih dari tiga tahun untuk proses itu saja. Bagaimana proses menulisnya? Tidak lebih dari dua bulan!
Saya sudah menghasilkan lebih dari 80 judul buku nonfiksi. Semuanya adalah hasil riset. Sebagian besar hasil membaca buku, literatur, dokumen, dan wawancara mendalam. Sebagian lagi hasil dari mengamati dan mendalami. Sebagian sisanya berdasarkan observasi dan pengalaman pribadi.
Jadi, sesungguhnya kita sudah melakukan riset setiap saat. Tinggal disadari saja lalu diperkaya dan lengkapi, sebagai bahan kita untuk menulis. Yang penting, tidak boleh tidak, setiap menulis harus melalui riset dan pengumpulan bahan yang lengkap. Jangan sampai tulisan kita sarat bohong dan banyak bolong.
(Dodi Mawardi)

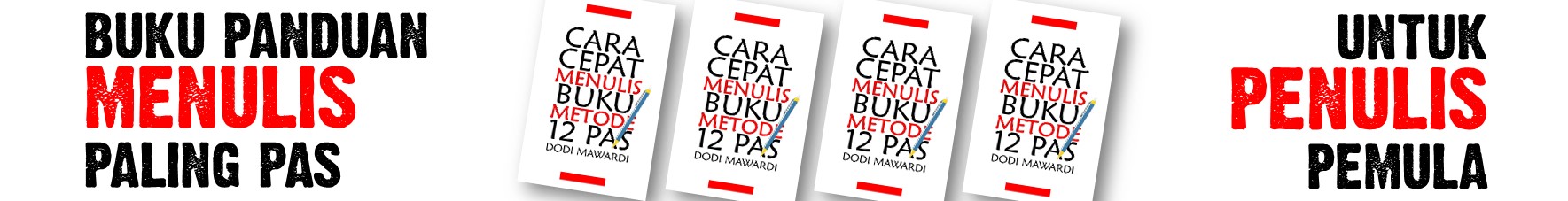






No Responses